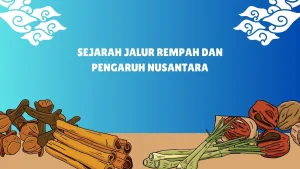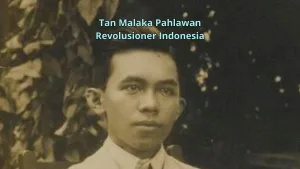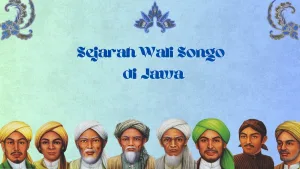WWW.GOLANNUSANTARA.COM – Sahabat Golan, tahukah kamu bahwa di Kalimantan pernah muncul tokoh yang mengubah wajah perlawanan rakyat? Pangeran Antasari, kelahiran 1809 di Kayu Tangi, Kesultanan Banjar, dikenal sebagai sosok karismatik yang dijuluki Sultan Banjar selama masa Perang Banjar. Beliau bukan hanya pemimpin militer, tetapi juga simbol perjuangan rakyat Banjar dan Dayak dalam menghadapi kolonialisme Belanda. Artikel ini mengajak kamu menyusuri jejak perjuangannya dengan gaya informatif dan menyenangkan.
Latar Belakang dan Pemicu Perlawanan
Menjelang pertengahan abad ke-19, kekuasaan kolonial Hindia Belanda mulai ikut campur dalam urusan dalam negeri Kesultanan Banjar di wilayah Kalimantan Selatan. Salah satu pemicunya adalah penunjukan Sultan Tamjidillah II oleh Belanda, yang ditentang oleh banyak pihak karena dinilai tidak sah secara adat dan hukum Islam. Sosok yang seharusnya naik tahta, yakni Sultan Hidayatullah II, malah disingkirkan oleh pihak Belanda. Kondisi ini memicu keresahan rakyat dan memunculkan sosok Pangeran Antasari sebagai pemimpin yang dianggap mampu menyatukan kekuatan lokal.
Pada tanggal 25 April 1859, Pangeran Antasari memimpin penyerangan ke fasilitas tambang batu bara milik Belanda yang terletak di Pengaron. Aksi ini menjadi penanda resmi dimulainya Perang Banjar. Serangan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga taktis karena menargetkan sumber daya penting milik kolonial. Peristiwa ini mendapat dukungan luas dari masyarakat Banjar dan suku Dayak, yang telah lama mengalami tekanan dari kekuasaan kolonial.
Awal Perang dan Taktik Gerilya
Dalam menghadapi kekuatan militer Belanda yang unggul dalam persenjataan dan logistik, Pangeran Antasari menerapkan strategi perang gerilya. Ia membangun benteng-benteng pertahanan di daerah terpencil seperti Gunung Sulit, Guyu, Bayan Begok, dan Liang Umbung. Lokasi-lokasi ini dipilih karena medan geografisnya yang sulit dijangkau oleh pasukan Belanda, sehingga memberikan keuntungan bagi pasukan lokal.
Selain mengandalkan medan, Pangeran Antasari juga mengandalkan jaringan sosial dan budaya. Ia membangun kedekatan dengan suku Dayak lewat hubungan politik dan jalinan kekerabatan. Bahkan, dalam beberapa pertempuran, pasukan Dayak tampil sebagai garda depan, menunjukkan bahwa perjuangan ini bukan sekadar konflik kerajaan, melainkan gerakan rakyat lintas etnis.
Penobatan Pangeran Antasari sebagai Sultan Banjar
Setelah Sultan Hidayatullah II ditangkap dan dibuang oleh Belanda, kekosongan kepemimpinan di Kesultanan Banjar membuat rakyat dan tokoh adat mencari sosok pengganti. Pada 14 Maret 1862, Pangeran Antasari resmi dinobatkan sebagai Sultan Banjar dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Gelar ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya diakui sebagai pemimpin politik dan militer, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual umat Islam di wilayah tersebut.
Penobatan ini mempertegas kedudukannya dalam struktur kekuasaan dan memberikan legitimasi lebih kuat dalam memimpin perlawanan. Dalam posisinya sebagai sultan, ia meneruskan perjuangan dengan semangat jihad melawan penjajahan, yang dalam konteks saat itu diterima sebagai bentuk pembelaan terhadap tanah air dan agama.
Perang Skala Besar
Setelah menjadi sultan, Pangeran Antasari meningkatkan intensitas perlawanan. Ia memimpin sekitar 300-6.000 pasukan untuk menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, dan Barito. Salah satu keberhasilan besar penenggelaman kapal milik Belanda dalam pertempuran, yang diperkirakan adalah kapal Onrust, yang menunjukkan bahwa strategi militer Pangeran Antasari cukup efektif dalam menandingi kekuatan kolonial.
Namun demikian, Belanda tidak tinggal diam. Untuk membendung perlawanan, Belanda mengerahkan lebih banyak pasukan dan menggencarkan serangan dalam skala luas. Wilayah-wilayah yang menjadi basis perlawanan diserang habis-habisan. Meski mengalami tekanan berat, pasukan Pangeran Antasari tetap bertahan berkat dukungan rakyat dan jaringan logistik yang solid.
Pangeran Antasari Wafat Menjelang Kemenangan
Pada puncak perjuangannya, Pangeran Antasari jatuh sakit akibat cacar dan penyakit paru-paru. Ia wafat pada 11 Oktober 1862 di Bayan Begok dalam usia 53 tahun. Kepergian beliau menjadi kehilangan besar bagi rakyat Banjar dan Dayak yang telah menjadikannya simbol perjuangan. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di Banjarmasin, dan pada 11 November 1958 dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Banjar.
Meski telah tiada, semangat perjuangan tidak padam. Putranya, Muhammad Seman, melanjutkan perlawanan hingga tahun 1905. Ia menjadi pemimpin terakhir dalam upaya mempertahankan kedaulatan Kesultanan Banjar sebelum akhirnya gugur dalam pertempuran.
Pembelajaran dan Peninggalan Sejarah dari Pangeran Antasari
Warisan perjuangan Pangeran Antasari masih terasa hingga kini. Melalui Keputusan Presiden Nomor 06/TK/1968, beliau diakui secara resmi sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan dalam berbagai institusi seperti Universitas Islam Negeri Antasari di Banjarmasin, Korem 101/Antasari, dan bahkan pada uang logam Rp2.000 edisi tahun 2009.
Tak hanya itu, nilai-nilai perjuangan Pangeran Antasari juga diajarkan dalam buku pelajaran sejarah dan dikenang dalam berbagai peringatan hari pahlawan. Semboyannya yang terkenal, “Haram manyarah waja sampai kaputing,” menjadi moto perjuangan dan semangat tak kenal menyerah yang masih relevan hingga hari ini.
Pangeran Antasari Simbol Perlawanan dan Persatuan
Sahabat Golan, Pangeran Antasari bukan hanya tokoh militer atau sultan semata. Ia adalah representasi nyata dari kekuatan lokal yang bangkit melawan ketidakadilan. Perjuangannya menyatukan rakyat Banjar, suku Dayak, dan wilayah-wilayah sekitar dalam satu tekad bersama: melawan kolonialisme dan mempertahankan kedaulatan.
Kisahnya memberikan inspirasi bahwa keberanian, kecintaan pada tanah air, dan kemampuan membangun solidaritas adalah senjata paling ampuh dalam menghadapi tantangan besar. Dari benteng-benteng terpencil di Kalimantan Selatan, lahir suara perjuangan yang gaungnya terdengar hingga kini.